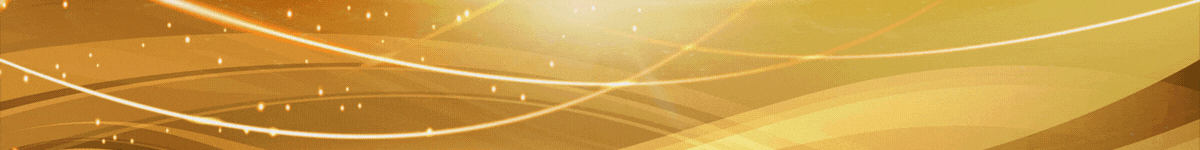Bicara tentang keris, tidak akan lepas dari identitas budaya masyarakat setempat yang melestarikannya. Kita mengenal Keris gaya Bali, Keris gaya Jawa Timur/Madura, Keris gaya Cirebonan, Keris gaya Jawa Mataraman (Surakarta dan Jogjakarta), Keris gaya Melayu (Sumatera, Sulawesi, Sumbawa), dan Keris gaya Lombok.
Masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri apabila dibahas secara bentuk fisiknya. Dalam tulisan ini, penulis secara khusus menampilkan Keris Bali, yang tidak akan tercerabut dari identitas budaya dimana keris itu lahir.
Keris Bali dan Lombok secara secara fisik memiliki banyak kemiripan, bahkan dapat dikatakan sama, karena dalam sejarahnya Kerajaan Karangasem pernah membawa pengaruh di Lombok di masa lalu. Dengan jangkauan wilayah ini, dari banyak orang Bali berada di Lombok kemudian mempengaruhi budaya asli Lombok.
Namun demikian, tetap saja, budaya lokal setempat tidak tergerus oleh proses asimilasi ini. Kemudian membentuk karakteristik yang unik bagi wilayah tersebut. Hal yang membedakan antara Keris Bali dan Keris Lombok apabila dibandingkan lebih dalam adalah detil karya seninya.
Misalnya dari sisi bilah, keris-keris Bali banyak menggali dari ornamen-ornamen candi maupun dari berbagai aspek yang membawa pengaruh dari sisi spiritual masyarakat Bali sendiri. Kemudian dari sisi warangka (sarung keris), seorang Meranggi (perajin warangka) di Bali memiliki keahlian yang diperoleh secara turun temurun, mereka juga seorang ahli tatah dan ukir perak yang tentu saja memiliki kekhasan sendiri.
Apabila kita sering melihat dan menikmati bentuk baik bilah, warangka maupun ornamen lainnya pada sebilah keris, maka akan lebih mudah untuk mendefinisikan mana Keris Bali dan mana Keris Lombok.
Dengan demikian Keris Bali mengandung peran yang kompleks dalam masyarakat dan telah berjalan di ruang dan waktu yang cukup panjang, sehingga memiliki karakteristik yang melekat dan menunjukkan keberadaannya sebagai identitas karya budaya yang khas masyarakat Bali.
Semakin dalam, keris bagi masyarakat Bali merupakan salah satu hasil budaya yang merangkum segala konsep dan manifestasi kehidupan masyarakatnya, baik konsep pemahaman yang transeden, konsep kehidupan sosial, maupun konsep teknomiknya sebagai benda kelengkapan hidup, yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Sebagai sebuah benda budaya penunjuk identitas, keris Bali memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari perjalanan sejarah seni tempa pusaka (keris) oleh Wangsa Pande, visualisasi bentuk fisik meliputi bilah, warangka, pendok, danganan, selut, wewer, dan lain-lain, pada gilirannya dapat kita lihat saat mengenakan bersama busana adat khas Bali yang luar biasa indahnya.
Pengantin truna dan truni Bali yang mengenakan busana adat Bali, truna akan membawa keris dengan danganan yang indah, sementara truni membawa kipas khas Bali yang tak kalah elegannya.
Berbicara tentang leluhur para wangsa Pande di Bali, menurut Kitab Brahma Pande Tatwa menjelaskan bahwa leluhur para Wangsa Pande merupakan keturunan dari para Mpu di Jawa. Sedangkan menurut Pustaka Bang Tawang aliran para Wamsa Pande atau Wangsa Pande merupakan penganut aliran Brahma yang memiliki pusat pemujaan disebut “Gedong Sinapa” atau “Gedong Batur Kemulan Kasuhun Kidul”.
Pada masa itu, Wangsa Pande merupakan golongan masyarakat khusus yang mengabdi kepada Raja, yang pekerjaannya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan logam termasuk senjata bagi keperluan kerajaan. Pekerjaan ini dilaksanakan secara turun temurun sehingga terbentuklah Trah Pande. Akan dianggap tabu apabila ada masyarakat selain Trah Pande mengerjakan pekerjaan sebagai pengolah logam.
Penggambaran pekerjaan para Pande dapat dijumpai dalam Kitab Kosawasrama, disebutkan bahwa pekerjaan seorang Mpu Pande memang selalu berkaitan dengan peleburan dan penempaan berbagai jenis logam, diceritakan antara lain sebagai berikut:
“20….. Kunang ikang salwiran ing katunu pinalu de sang Mpu Pande pratyekanya, yan kanaka drawa, akuning asari samunu rupanya, (yan salaka), yan ganaga abang tanpa sari rupanya, yan gangsa, akuning aputih tanpa sari rupanya”
“21…. parunggu akuning rupanya, yan lancing, akuning tanpa sari rupanya, yan wesi aroma ireng rupanya….”
(“terjemahan bebasnya….Adapun segala yang dilebur (dipanaskan) dan ditempa oleh Mpu Pande, misalnya emas kuning cemerlang berseri warnanya, kalau perak putih warnanya, kalau tembaga merah redup warnanya, kalau gangsa kuning keputih-putihan warnanya, kalau perunggu kuning kusam warnanya, kalau besi menyerupai rambut warnanya….”)
Periode Bali Kuno yaitu pemerintahan Raja Udayana merupakan periode awal perkembangan para Wangsa Pande di Bali. Meskipun sangat sedikit ditemukannya data yang berkaitan dengan seni tempa (keris) di Bali, namun keberadaan keluarga Pande dari prasasti kuno masih dapat ditemukan, antara lain: Prasasti Sukawana, Manuskrip Kuno Pande Bang Tawang, Prasasti Bulian, dan Prasasti Pura Kehen.
Hingga Periode Bali Madya yaitu era Kerajaan Majapahit, ditemukan Prasasti Tambelingan yang menceritakan kehendak raja untuk melindungi dan mengembalikan keberadaan Wangsa Pande di Bali seperti sediakala, setelah bercerai berai usai invasi Majapahit di Bali. Di masa ini juga dikenal seorang Mpu dari Madura yang menjadi pendeta di Istana Gelgel.
Mpu tersebut dikenal dengan sebutan Pujangga Kayu Manis atau juga disebut Mpu Brahma Raja. Keberadaan Sang Mpu Brahma Raja ini diceritakan dalam Babad Brahma Pande Tatwa (abad XVI) dan Babad Dalem (abad XVII). Lebih jauh diceritakan bahwa Mpu Brahma Raja tinggal di Desa Kayu Manis dan menikah dengan Diah Amertama. Dari perkawinan tersebut lahir putra dan putri yang bernama Brahma Rare Sakti yang mahir dalam Ilmu Kepandean dan Dyah Kencana Wati yang mahir dalam membuat perhiasan.
Raja Majapahit di Bali yaitu Dalem Ketut Smara Kepakisan selain dikawal oleh para Arya juga didampingi seorang Mpu yang bernama Mpu Siwa Saguna. Sampai pemerintahan beralih kepada Dalem Waturenggong, para Wangsa Pande mendapat porsi yang lebih banyak dalam sumbangsih karya khususnya keris di Bali, karena legitimasi Raja di Bali semakin besar pasti di dukung oleh fasilitas persenjataan yang memadai. Konon di masa-masa inilah wangsa Pande di Bali mencapai masa keemasan dan berkembang hingga kini.
- Karakteristik Bilah Keris Bali
a. Ukuran Bilah
Secara garis besar ukuran bilah keris Bali dibedakan menjadi 2 (dua) gaya yaitu Gaya Jawa dan Gaya Bali. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
- Keris Bali gaya Jawa merupakan keris kuno dimana paling akhir merupakan peninggalan masa Majapahit. Ukuran panjangnya 33-35 cm, kualitas besinya terbaik dengan tempaan matang dan kokoh bertaksu luar biasa. Pamornya terang dan bersih meskipun tampak sederhana, jumlah lipatan saat ditempa juga lebih kaya. Bangunan bilahnya juga cenderung merunduk, sopan dan tenang namun
- Keris Gaya Bali merupakan keris setelah era Majapahit dengan ciri fisiknya memiliki ukuran panjang 35-45 cm. Bilahnya tegak, tegas dan tebal sehingga tampak kuat dan tajam. Jumlah lipatan lebih sedikit di bandingkan keris Bali gaya Jawa. Finishing lebih halus dan mengkilat karena di-sangling yaitu digosok menggunakan batu.
b. Bentuk Bilah
Menurut buku Keris Bali Bersejarah karya Pande Wayan Suteja Neka dan Basuki Teguh Yuwono, tipologi bentuk keris Bali dibagi menjadi 4 bentuk dasar antara lain:
- Keris bentuk Luk (berkelok/berlekuk) mulai dari luk 3 hingga luk 29.
- Keris bentuk Lajer (lurus) mulai dari ricikan yang sederhana hingga jumlah ricikan yang lengkap dan
- Keris bentuk pedang dimana penggunaannya dapat disabet maupun ditusuk. Keris jenis ini hanya ada di Bali dan Lombok, sehingga dianggap tidak lazim di daerah lain seperti di Jawa.
- Keris bentuk campuran antara keris luk, lajer dan pedang. Keris jenis ini biasanya dihias dengan perak yang indah dan dijadikan ageman kerabat kerajaan.
c. Bentuk Gandik
Ragam bentuk gandik yang menunjukkan karakteristik bilah keris Bali di kelompokkan menjadi 3 yaitu:
- Gandik Polos, yaitu gandik yang polos tanpa dihias rericikan
- Gandik Motif, yaitu gandik yang dihias dengan cunguh gajah, kembar didur, panji pengantin, cunguh gajah pued dan lain-lain.
- Gandik Gana, yaitu gandik yang dihias figur tertentu misalnya singa, naga, gajah, Batara Kala, manusia bertapa hingga perkembangannya figurnya adalah pahatan ornament candi, pewayangan dan mitologi.
d. Bentuk Reringgitan
Greneng yang lebih popular disebut dengan istilah reringgitan di Bali, lebih banyak ragamnya dibandingkan dengan keris Jawa. Hal ini terjadi karena lebih leluasanya para Mpu dalam mengeksplorasi baik bentuk bilah maupun bentuk gandik keris Bali dibandingkan pakem keris Jawa. Munculnya gandik keris motif Gana semakin menambah variasi dalam bentuk reringgitan pada keris Bali. Sehingga keris Bali terkesan lebih dinamis dibanding keris Jawa yang lebih taat pada pakem keris sepuh, sementara keris di luar pakem dianggap sebagai keris kalawijan.
e. Bentuk Ganja
Ganja pada keris adalah bagian yang seolah merupakan alas dari kedudukan bilah keris. Pada tengah ganja berlubang untuk dilewati pesi yaitu tangkai bilah keris. Pada keris antara bilah dan ganja merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan sebagai symbol lingga yoni dan ada pula keris yang antara bilah dan ganja menjadi satu disebut ganja iras.
Ragam bentuk ganja pada Keris Bali antara lain:
- Ganja Keris Nguceng Mati, banyak di jumpai pada keris-keris Bali gaya Jawa yaitu keris-keris sepuh era Majapahit.
- Ganja Keris dengan bentuk Kepala Buweng, adalah keris-keris setelah era Majapahit.
- Ganja Keris dengan kepala besar, banyak dijumpai pada keris-keris era Kerajaan Buleleng dimana mendapat pengaruh dari Kerajaan Blambangan di Banyuwangi.
- Ganja Keris kepala ganja runcing, banyak dijumpai pada keris-keris Bali yang beredar saat ini.
- Ganja Keris dengan bentuk ganja rata, hanya dijumpai pada keris bali yang berbentuk keris pedang.
f. Bentuk Pamor
Karakteristik keris Bali dapat dilihat dari tata pamor yaitu hiasan pada bilah keris yang berwarna putih. Pamor pada keris Bali tidak sedetil pada keris-keris di Jawa dan Madura yang lebih kaya dan banyak ragamnya. Di Bali lebih banyak keris dengan pamor Wos Wutah, namun aspek pola garapnya lebih tegas dan tajam dibandingkan keris Jawa, karena memang secara bilah selain lebih panjang juga lebih tebal sehingga Pande di Bali lebih leluasa dalam memainkan kruwingan maupun sogokan.
- Karakteristik Warangka Keris Bali
Di Jawa ada istilah Curiga Manjing Warangka yang dimaksudkan sebagai simbolisasi Manunggaling Kawula lan Gusti yaitu konsep menyatunya hati dan pikiran manusia sehingga pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Apabila manusia mampu menjadikan kebaikan sebagai sesuatu yang harus dikedepankan, berkomitmen menaklukkan ego serta memiliki kepasrahan pada kebesaran Ilahi, maka Tuhan pun akan memberikan ketenangan, kedamaian dan keindahan bagi umat manusia.
Dengan konsep Manunggaling Kawula lan Gusti ini maka akan semakin memahami Sangkan Paraning Dumadi, yaitu berasal dari mana dan kembali kemana manusia ini diciptakan, sehingga jiwa-jiwa yang semula penuh keangkuhan, kesombongan, nafsu mau menang sendiri dan selalu merasa paling benar dapat dihindarkan, karena kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan YME.
Sangkan Paraning Dumadi dalam filosofi Kejawen mengajarkan bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita harus mendekati nilai-nilai luhur ketuhanan. Nilai-nilai luhur ketuhanan antara lain adalah jujur, adil, tanggung-jawab, peduli, sederhana, ramah, disiplin dan komitmen.
Warangka dan bilah merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Warangka tanpa bilah adalah hampa, sedangkan bilah tanpa warangka ibarat manusia telanjang tanpa busana. Bagi masyarakat Bali, memperindah bilah keris dengan warangka merupakan suatu keharusan agar wesi aji (besi suci) mendapatkan rumah, sehingga makna filosofis, makna simbolis maupun makna spiritual dari bilah keris akan semakin tajam dalam mempengaruhi sendi-sendi kehidupan.
Beberapa bentuk warangka Keris Bali antara lain:
- Warangka Kekandikan
- Warangka Sesrengatan
- Warangka Batun Poh (Gegodoan)
- Warangka Kojongan
- Warangka Jamprahan/Bancihan
- Warangka Ukir
Bahan Warangka dan Hulu/Danganan pada Keris Bali, antara lain:
- Gading Gajah
- Geraham Gajah Purba
- Taring Walrus
- Tulang Ikan Duyung
- Tulang Ikan Paus
- Tanduk Rusa
- Kayu Katimaha
- Kayu Mentawas
- Kayu Eboni
- Kayu Angsana Keling
- Kayu Tri Kancu
- Kayu Purnama Sadha
- Kayu Santigi
- Kayu Trembalo
- Kayu Nagasari
- Kayu Majagau
- Kayu Pelem Pakel
- Kayu Gaharu
- Emas
- Perak
- Kuningan
- Suasa
- Tembaga
- Perunggu
Hulu/Danganan dan Warangka Keris Bali akan semakin indah apabila diberi hiasan logam mulia dan ukiran dari bahan perak. Batu mulia yang banyak dipergunakan antara lain:
- Berlian/Intan
- Merah Siam/Ruby
- Blue Safir
- Bangsing
- Berbagai batu local yang layak
- Keris dan Masyarakat Bali
Keris sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bali baik yang tinggal di Bali maupun yang di perantauan. Namun khusus keris Bali, masih menurut buku Keris Bali Bersejarah karya Pande Wayan Suteja Neka dapat secara garis besar di bagi sebagai berikut:
- Sebagai Kelengkapan Sarana Ritual dan Spiritual, dimana konsep religi masyarakat Bali mengenal Panca Yadnya (5 Jenis Upacara) yaitu Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Bhuta Yadnya, Pitra Yadnya, dan Resi Yadnya)
- Sebagai Identitas Adat Masyarakat Bali, dari sisi bentuk fisik keris akan dapat diketahui bahwa keris Bali memiliki ciri dan atribut tertentu, dan pas apabila menjadi pelengkap busana adat Bali
- Sebagai Senjata Pusaka dan Perlindungan Diri, dahulu memang keris Bali adalah salah satu senjata untuk mempertahan diri, namun saat ini sudah menjadi benda koleksi yang memiliki aspek psikologis.
Pada pertunjukkan tari seperti Calon Arang, tari barong, tari baris dan lain-lain, penari pria pada umumnya mengenakan keris. Saat di tengah tarian, ada isitilah ngunying yaitu menusukkan keris ke dada dan lehernya sendiri. Karena sangat digemari baik oleh wisatawan local maupun wisatawan mancanegara sehingga kemasannya pun lebih modern dan tidak se-sakral pada upacara keagamaan.
Di Bali dalam satu tahun diadakan Upacara Tumpek Landep yang jatuh pada hari Sabtu Wuku Landep, dimana upacaranya selain mengucapkan rasa syukur kepada Sang Hyang Aji Pasupati sebagai simbolisasi Tuhan Yang Maha Esa juga agar keris yang dimiliki dapat memberikan penajaman pemikiran, penajaman wawasan dan penajaman dalam menelaah masalah untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
Masih berlaku juga Ketika Upacara Mepandes (potong gigi), orang tua memberikan hadiah berupa keris kepada seorang anak laki-laki sebagai symbol kedewasaan. Atau pada saat pawiwahan (upacara perkawinan), para orang tua memberikan hadiah keris kepada mempelai pria sebagai symbol kemandirian dan telah mendapat mandat serta tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.
Masih banyak kegiatan masyarakat Bali yang berkaitan dengan keris, seperti misalnya Pecalang yang mengenakan keris dipinggangnya, upacara pengayu-ayu guna mengusir hama tikus, pada upacara ngaben juga ada kalanya para pria mengenakan keris di pinggangnya. Masih banyak lagi apabila di detilkan seperti di beberapa desa saat hadir di acara Sangekepan (Rapat Desa) ada kalanya membawa keris.
- Budaya Keris di Bali era Kamardikan
Di masa penjajahan Belanda dan Jepang, Wangsa Pande di Bali mengalami masa-masa suram, karena aturan larangan penjajah, sehingga banyak diantara mereka terpaksa meninggalkan profesinya sebagai pembuat senjata khususnya keris, pedang, tombak dan lain-lain.
Untuk mempertahankan hidup, para Wangsa Pande pun beralih mata pencaharian menjadi pegawai, menjadi pengusaha, berdagang dan lain-lain. Keahlian yang semula turun temurun dimiliki oleh Wangsa Pande pun akhirnya terputus di generasi setelahnya. Meskipun masih ada yang tetap berkarya, itupun hanya sebatas sebagai pengrajin alat-alat pertanian seperti sabit, cangkul, parang dan lain-lain.
Pada era setelah Indonesia merdeka dari cengkeraman penjajah tahun 1945, atau era Kamardikan, beberapa orang Wangsa Pande mencoba kembali untuk membuat senjata, khususnya keris. Namun keris yang dihasilkan sangat jauh berbeda dan mengalami kemunduran dari sisi estetika dan nilai artistik dibandingkan dengan karya para leluhurnya. Kemunduran dari karya Pande era kamardikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
- Terputusnya generasi pembuat keris pada Trah Pande, sehingga terputus pula warisan dari sisi teknologi, khususnya teknis pencampuran logam besi, baja dan nikel yang baik untuk pembuatan pamor pada bilah keris.
- Tidak tersedianya bahan untuk membuat keris yang memiliki kualitas bagus, karena sentra-sentra pengolahan logam seperti besi dan baja juga ikut hancur saat penjajah menguasai Bali.
- Wangsa Pande yang telah beralih profesi di luar pembuatan keris seperti yang dilakukan oleh leluhurnya, enggan kembali untuk membuat keris karena selain karena minimnya keahlian juga kesulitan memasarkan hasil karyanya.
- Perhatian pemerintah untuk membekali para Trah Pande misalnya berguru (ngangsu kaweruh) Ilmu Pembuatan Keris ke Jawa dan Madura masih minim.
- Membanjirnya keris-keris baru gaya Bali karya pengrajin keris dari Jawa dan Madura di pasar keris Bali semakin menyurutkan langkah para Trah pande berkarya kembali.
Trah Pande yang masih terus berkarya di era Kamardikan di tengah gempuran keris-keris gaya Bali buatan Jawa dan Madura antara lain:
- Pande Ketut Mudra asal Klungkung, leluhurnya berasal dari Majapahit yang mengiringi Mahapatih Gajah Mada ke Bali dan mengabdi kepada Kerajaan Klungkung.
- Pande Yuga Wardiana adalah putra dari Pande Nyoman Budiana yang merupakan cucu dari Jro Mangku Pande Ketut Sandi (almarhum) asal Banjar Tatasan, Kota Denpasar.
- Pande Made Sumardiyasa, dimana leluhurnya adalah Pande keris di Kerajaan Karangasem, saat ini tinggal di Sanur.
- Pande Putu Sunarta dari Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- Pande Made Gede Suardika yang mendapat dukungan dari Puri Kesiman dan mendapat bimbingan dari AA Ngurah Gede Kusuma Wardana untuk berguru ke Besalen Brojobuono Solo, beralamat di Jl. Kenyeri Denpasar.
- Pande Ketut Margita asal Banjar Batusangian, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, pernah berguru secara private dari para pengrajin keris Madura (termasuk Cak Rafiq Kamarogan) atas prakarsa Paguyuban Semar Sanjiwata untuk membina para Pande di Bali.
- Pande Mangku Gede Sutama dari Desa Celuk, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar.
- Pande Subrata dari Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Pande Ketut Nala dari Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
Seperti dijelaskan di awal bahwa berbicara keris Bali tidak hanya berkaitan dengan bilahnya saja, karena untuk memperindah keris juga memerlukan warangka, danganan maupun hiasan batu permata dan ornamen ukir perak.
Profesi ini masih lestari secara turun temurun dan tetap menghiasi dunia penciptaan keris di Bali. Meskipun pada praktiknya para pengrajin ini juga menggantungkan hidupnya dengan berdagang keris dan ikut serta berbursa meramaikan pasar tosan aji di Indonesia.
Berikut adalah Daftar Meranggi (pembuat warangka yang masih aktif) di Bali:
- Nyoman Yutdiarta dari Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Bali, merupakan salah satu pengrajin warangka keris Bali yang produktif. Keahliannya dalam membuat warangka berasal dari orang tuanya yaitu Made Dana yang juga memiliki galeri dan bengkel keris yang bernama Dana Keris.
- Made Ardika dari Desa Batuan Kecamatan Sukowati Kabupaten Gianyar Bali, merupakan putra dari pengrajin warangka Wayan Rajin dan cucu dari Wayan Roja. Spesialisasi karya Made Ardika adalah gaya Sesrengatan yang oleh masyarakat perkerisan Bali dianggap terbaik.
- Ketut Jerut dari Desa Batuan Kecamatan Sukowati Kabupaten Gianyar Bali, juga merupakan Meranggi yang jempolan dan karyanya banyak dipesan keluar Bali.
- Wayan Sidastra (Moyo) dari Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Bali, merupakan Meranggi muda sedang naik daun, yang juga anggota Paguyuban Semar Sanjiwata.
Berikut adalah Daftar Pembuat Hulu/Danganan Keris yang masih aktif di Bali:
- Ida Bagus Pastika adalah maestro yang karyanya dikenali hingga ke mancanegara. Karya buatan Pekak (Kakek) ini sangat halus, detil dan berkarakter sehingga banyak diburu oleh kolektor keris Bali.
- I Wayan Tika, juga salah satu maestro danganan keris dari Bangli
- I Wayan Sandi, dari Bangli
- Ida Bagus Pudja dari Tampaksiring, Gianyar.
- Nyoman Bagya Turi Denpasar.
- Ketut Nik Suyasa dari Desa Lodtunduh, Ubud Kabupaten Gianyar
- Dewa Lumbung dari Tampaksiring, Gianyar.
- I Wayan Sujarwa dari Tampaksiring, Gianyar.
- Pande Nyoman Sugita, dari Gianyar
- Wayan Suwastawa, dari Gianyar
- Pekak Kruntung dari Denpasar.
Berikut adalah Daftar Pembuat Pendok Keris yang masih aktif di Bali:
- Made Pada berasal dari Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. Keahliannya selain membuat pendok untuk menghias warangka-warangka keris Bali juga menghias hulu/danganan baik model togogan, kusia, gerantim, cenangan, cekahan, loncengan maupun bebondolan.
- I Wayan Sugena, juga berasal dari Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
- Kadek Sukarsana (Praven) dari Jl. Nusantara Bangli.
- Pande Made Punarbawa dari Bangli.
- Pande Dangan dari Bangli.
- Pande Tagel dari Bangli.
- I Kadek Dedik Pravena dari Celuk, Sukowati, Gianyar.
- I Nyoman Julit dari Celuk, Sukowati, Gianyar.
Materi: dari Buku Keris Bali Kontemporer
Ditulis oleh: Begawan Ciptaning Mintaraga
Bidang Edukasi Senapati Nusantara
Penglingsir Semar Sanjiwata Bali
Anggota Dewan Pembina Panji Beber Kota Bontang